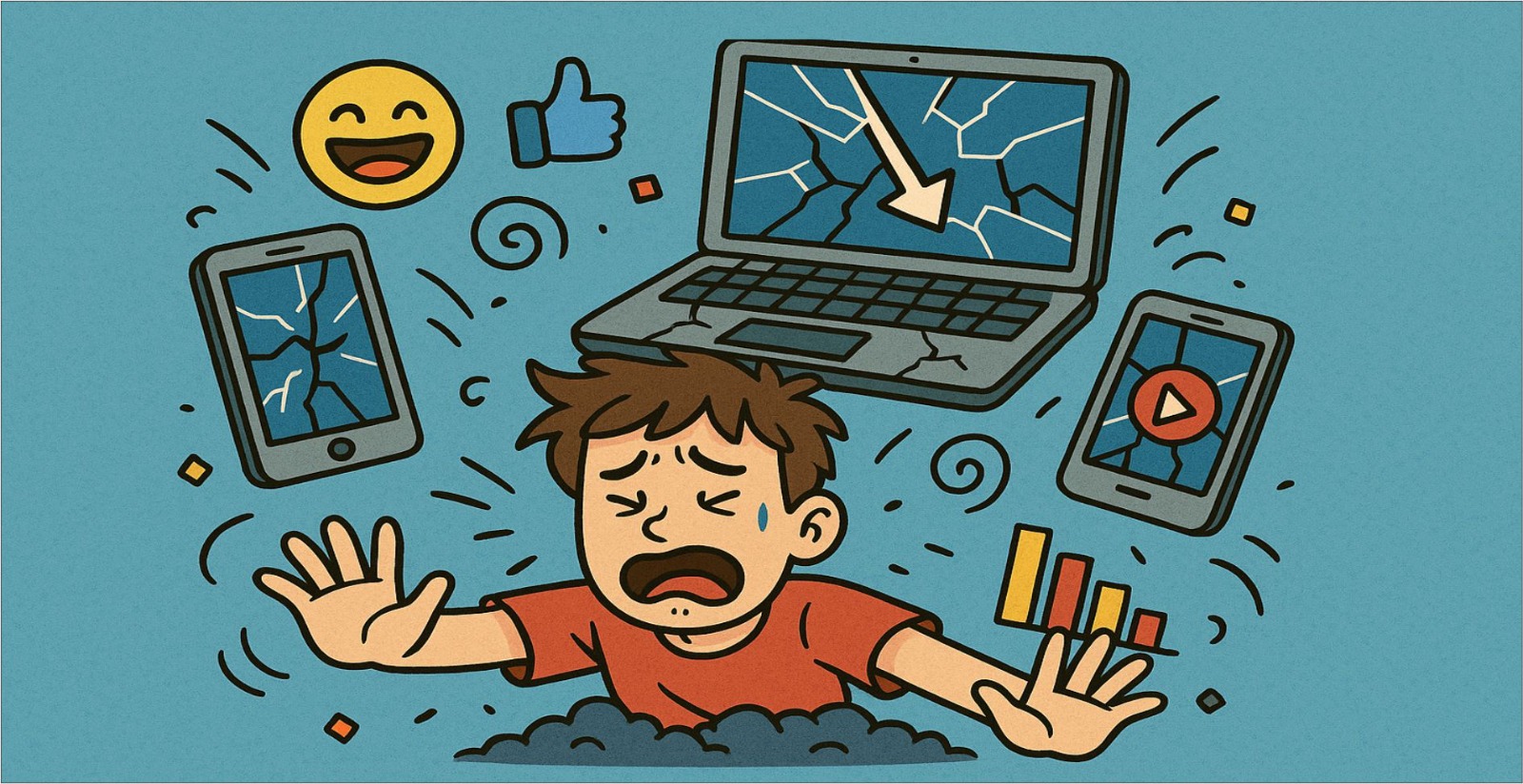......”Dan pergaulilah mereka (para istri) dengan cara yang patut (ma’ruf). Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”
(QS. An-Nisa’: 19)
Aku telah menjadi saksi banyak kisah: tentang cinta yang tumbuh, lalu layu, dan kadang, mati tanpa suara. Seperti kisah Adit dan Rani ini ( bukan nama asli ). Mereka datang ke BP4 ( Badan Pembinaan Penasehatan dan pelestarian Perkawinan ) bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dilepaskan, dari luka yang tak kunjung sembuh.
Hari itu, Adit dan Rani duduk bersamaku. Mereka pasangan muda, usia mereka belum genap 30 tahun. Tampan dan cantik, rapi, tapi kosong. Bukan karena tidak ada cinta, melainkan karena cinta mereka kehabisan ruang untuk tumbuh.
Rani yang pertama membuka suara. “Kami ingin bercerai, Bu…”
Alasannya perlahan mengalir. Tentang rumah tangga yang dingin, tentang malam-malam sunyi tanpa pelukan, tentang sentuhan yang tak lagi ada. Tentang Adit yang terlalu sibuk dengan hobinya, game online dan dunia digitalnya. Dan akhirnya, tentang Rani yang tergelincir, mencari pelarian dalam pelukan orang lain.
"Aku tahu itu salah," kata Rani dengan air mata. "Tapi aku kesepian, Bu. Setiap malam hanya melihat dia dengan headset, tertawa di depan layar. Aku tidur sendiri. Aku bangun sendiri."
Adit, di sisi lain, merasa dikhianati. Dua tahun lalu, ia memergoki Rani bersama pria lain. Sejak saat itu, tubuh dan pikirannya menolak keintiman. Trauma membuatnya menjauh. Sentuhan Rani justru membuatnya sesak.
"Aku nggak bisa," ujar Adit. "Setiap kali dia dekati aku, bayangan itu muncul lagi."
Mereka telah mencoba segala upaya medis dan psikologis. Tapi tak juga berhasil. Dan sekarang, mereka menyerah.
Aku mendengarkan dalam diam. Sebagai seorang muslim, aku tak bisa mengabaikan bahwa hubungan biologis antara suami dan istri bukan sekadar pelengkap dalam rumah tangga, tapi bagian dari ibadah dan hak masing-masing.
Aku berkata pelan, “Tahukah kalian, bahwa dalam Islam, kebutuhan biologis suami-istri bukan hanya urusan dunia, tapi juga bagian dari mu’asyarah bil ma’ruf - berinteraksi dengan cara yang baik dalam rumah tangga?”
Lalu aku kutipkan ayat:
“...dan pergaulilah mereka (para istri) dengan cara yang patut (ma’ruf). Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”
(QS. An-Nisa’: 19)
Aku menjelaskan dalam tafsir ayat ini, ulama menyebutkan bahwa "mu'asyarah bil ma’ruf" mencakup aspek emosional, ekonomi, dan juga biologis. Suami-istri saling berkewajiban menjaga dan memenuhi hak-hak jasmani dan rohani masing-masing.
“Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu sang istri menolak, dan sang suami tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Tentu, hadits ini bukan untuk menyalahkan perempuan secara sepihak, melainkan menunjukkan betapa penting dan seriusnya urusan kebutuhan biologis dalam rumah tangga. Demikian pula, jika suami yang menolak tanpa sebab syar’i, maka ia juga menzalimi hak istrinya.
Dalam kasus Adit dan Rani, hubungan mereka mulai retak bukan hanya karena perselingkuhan, tapi karena kebutuhan batin yang tidak terpenuhi dalam waktu yang lama. Kebutuhan yang Allah ciptakan sebagai fitrah manusia, bukan sesuatu yang tabu, melainkan perlu dipelihara.
“Ada hak istri yang terabaikan, dan ada kepercayaan suami yang dihancurkan,” kataku pelan. “Dan ketika itu tak disembuhkan bersama, rumah akan runtuh.”
Rani mengangguk. “Aku sudah mencoba bicara... tapi sepertinya kami terlalu tenggelam dalam dunia kami sendiri. Aku ingin disayang, bukan diabaikan.”
Adit menggenggam tangan sendiri, wajahnya penuh sesal. “Aku pikir selama aku bekerja dan menghasilkan, itu cukup. Aku nggak sadar kalau aku kehilangan istriku pelan-pelan…”
Aku ingatkan mereka pada sabda Nabi ﷺ yang indah:
"Sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian pun memiliki hak atas kalian."
(HR. Tirmidzi)
Hubungan suami-istri, termasuk hubungan biologis, adalah amanah. Ia bukan sekadar pemenuhan nafsu, tapi cara mengikat cinta, mengurangi kesedihan, dan menjaga kesetiaan.
Tapi kenyataan kadang tak selalu sejalan dengan harapan. Trauma Adit terlalu dalam. Luka Rani pun tak mudah pulih. Mereka mencoba bertahan, tapi akhirnya menyerah.
Mereka memutuskan bercerai, bukan karena saling membenci, tapi karena menyadari bahwa cinta tak cukup bila tubuh dan jiwa tak lagi selaras. Mereka ingin sembuh, tapi tak bisa bersama. Dan dalam Islam pun, Allah memberikan jalan keluar saat rumah tangga menjadi tempat penderitaan, bukan ketenangan.
“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana.”
(QS. An-Nisa’: 130)
Hari itu, Adit dan Rani meninggalkan ruang BP4 ( Badan Pembinaan Penasehatan dan pelestarian Perkawinan ) dengan tenang. Tak ada amarah. Hanya ada perpisahan yang ikhlas, dan pelajaran yang tertinggal.
Dari mereka kita dapat belajar bahwa kebutuhan biologis bukan sekadar urusan ranjang, tetapi bagian penting dari ikatan spiritual dan emosional dalam pernikahan. Ketika aspek ini terabaikan, dan komunikasi tidak terbangun, maka rumah bisa retak perlahan. Sebaliknya, ketika pemahaman keagamaan dan pendekatan keilmuan dipadukan, maka konflik rumah tangga bisa dihadapi dengan lebih bijaksana, meski pada akhirnya perpisahan menjadi pilihan terbaik. Dalam Islam, bahkan perpisahan pun bisa menjadi bentuk kasih sayang, ketika itu membawa pada kebaikan dan kesembuhan jiwa bagi keduanya.
Oleh : Ernawati, S.Ag // Penyuluh Agama Islam // Kantor Kementerian Agama Kota Malang